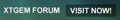“Yah, kamu boleh saja berhenti bekerja, asalkan kamu sanggup hidup dengan gajiku yang tak seberapa,”
Dari situ naluriku mulai bicara. Rasanya ada sesuatu yang salah dengan reaksi suamiku. Bukankah ia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk memulai berbagai usaha? Dan ketika kutanya mengapa ia gagal, ia berkata,
“Semua gara-gara kamu tidak cukup mendukungku!”
Lalu apakah namanya setelah begitu banyak tabunganku yang telah digunakannya untuk memulai usaha dan membeli ini dan itu? Ah, baiklah…barangkali dukunganku belum cukup banyak. Membeli rumah, tanah, dan sebagainya,belum lagi cukup untuk mendukungnya.
Tapi dalam hatiku aku bertanya tanya, bukankah sikap seperti itu adalah sikap laki-laki yang tak bertanggung jawab? Bukankah semestinya ia berusaha keras untuk menyatukan kami dalam satu atap, dan bukannya bertahan untuk terus berlama-lama hidup terpisah? Aneh….
Tapi kutekan semua prasangka itu dan selalu ku meminta ampun pada Allah, setiap kali pikiran seperti itu muncul. Mungkin tak ada yang aneh dalam diri suamiku.
Itu hanya perasaanku saja. Maka aku harus bersabar. Tapi aku tetap ingin lepas dari situasi itu. Aku tetap ingin menjadi ratu dalam rumah tanggaku. Aku ingin berada di rumah untuk anak-an akku, seperti perempuan lainnya.
Maka satu pelajaran yang kupetik dari situasi itu adalah, bahwa akulah satu-satunya yang bisa melepaskan diriku dari himpitan kesulitan ini. Akulah yang harus berusaha.
Maka aku bekerja lebih keras, mendorong suamiku untuk membuka bisnis dan usaha sampingan dengan memberinya modal. Sementara itu, hidup kami makin aneh saja. Pada suatu titik, suamiku mulai terlihat berbeda. Bila kami bertemu, entah karena aku dan anak-anak pulang ke daerah kami, atau ia yang berkunjung ke te mpat kami, ia sering tak mempedulikanku, memarahiku karena hal-hal remeh seperti salah meletakkan pulpen atau kertas kerja miliknya, terlambat membayar tagihan, terlambat membukakan pintu gerbang, dan sebagainya.
Tentu aku tak mengatakan bahwa diriku benar. Aku memang salah, sungguh tak kutampik kenyataan itu.Kekurangrnarnpuanku menjadi perempuan dan istri yang cermat dalam mengatur barang-barang nya, efisien dalam mengatur waktuku, memang tak bisa dibenarkan.
Masalahnya adalah, aku bekerja seharian di sebuah perusahaan swasta asing milik warga negara Jepang, yang terkenal disiplin dan ketat dalam mengatur waktu kerja.
Maka, aku harus mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga, yang mengurusi segala tetek bengek rumah tangga kami, termasuk keperluannya, yang semuanya di bawah instruksiku. Malangnya, pembantuku ini tidaklah selalu bisa bekerja dengan baik. Ada kalanya ia membuat begitu banyak kesalahan. Malangnya lagi, setiap kesalahan yang diperbuatnya, akan merupakan bencana bagiku, karena begitu aku pulang dari bekerja, dalam keadaan lelah luar biasa, aku akan menerima segala amarah dan omelan dari suamiku.
Baiklah! Aku ini perempuan. Sudah menjadi tugasku untuk mengatur semua urusan rumah tangga. Ketika pembantu rumah tanggaku alpa, maka itu adalah salahku.
Tanggung jawabku! Aku terima. Aku pun terima ketika suamiku menegurku dengan cara mendiamkanku berlama-lama, tak menerima maafku meski aku menangis dan menyembah. Ketika itu kupikir, baiklah…aku memang salah.Tentu seorang suami berhak memarahi istrinya. Maka aku pun membiarkannya mendiamkanku beberapa hari bahkan ber minggu-minggu. Hingga lama-lama aku terbiasa dengan cara itu, bahkan ketika ia memdiamkanku selama beberapa bulan karena kesalahan yang tak jelas.Kupikir, sebagai istri aku harus menurut dan menerima. Barangkali memang begitu jugalah para suami lainnya ketika memarahi istrinya.
Aku tak pernah berpikir untuk melawan,aku malah berpikir bagaimana cara menebus dan memperbaiki semua kesalahanku. Bagaimana cara membuatnya tenang dan mau berbaik-baik denganku. Bagaimana caranya agar ia mencintaiku lagi.
Kupikir, barangkali ego kelelakiannya telah kusi-nggung sebab aku berpenghasilan 5 kali lipat lebih besar dibandingkan penghasilannya.Barangkali ia cemburu dan begitulah caranya menyalurkan kecemburuannya, tapi di satu pihak ia tak sanggup menghidupi kami.
Berpikir seperti itu membuatku kasihan padanya. Maka kuputuskan untuk menyerahkan seluruh gaji dan bonus bonus yang kuperoleh dari perusahaan padanya. Aku hanya mengambil seperlunya untuk keperluan seharihari rumah tanggaku. Selebihnya, kubiarkan ia mengelola keuanganku.
Kupikir dengan begitu ia akan merasa dipercaya dan tahu bahwa sungguh aku tak pernah memikirkan uang. Yang penting bagiku adalah kami semua bahagia.
Akupun setuju ia membeli tanah, rumah, dan banyak lagi yang lainnya. Aku juga makin mendukung sepenuhnya dan membebaskannya menggunakan ua ng hasil kerjaku untuk berbisnis. Meski, setiap kutanya apa hasilnya ia akan marah dan mendiamkanku untuk beberapa lama.
Semakin ia marah dan makin lama mendiamkanku, semakin aku merasa harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahanku. Entah mengapa aku selalu merasa bahwa semua sikapnya itu adalah reaksi dari perbuatanku, dari kesalahan yang kubuat. Maka akupun makin mencoba membeli perasaannya, cintanya. Kubelikan ia hadiah-hadiah, yang seringkah malah tak cocok dengan seleranya dan menjadi kemarahan lainnya. Kubujuk ia untuk pergi ke toko bersamaku dan memilih baju atau apa saja kesukaannya.
Sungguh aku makin giat berusaha mendapatkan kembali cintanya.
Dalam hati, sering muncul pertanyaan, “Mengapa suamiku sepertinya membenciku? Apakah ia tidak mencintaiku lagi?” Lalu, sisi hati yang lain membantah,
“Tentu ia mencintaimu. Bukankah ia suamimu?”. “Tapi jika memang ia mencintaiku, mengapa ia selalu bersikap rnernusuhiku?” kata sisi hati lainnya.
Ku bertahan. Bahkan hingga aku hamil anak ke empat.
Kupikir, dengan memberinya seorang anak lagi, tentu ia akan senang dan sembuh dari semua kemarahannya.
Mempersembahkan seorang anak lagi, tentu akan merekatkan kembali hati kami. Ingin kutebus cintanya dengan anak kami yang keempat ini.
Tapi ternyata, harapanku tinggal harapan. Suamiku makin menjadi-jadi. Ia mendiamkanku berbu lan-bulan karena kesalahan-kesalahan kecil atau bahkan tak jelas apa yang membuatnya marah padaku. Bahkan dalam keadaan aku hamil tua dan kemudian melahirkan, ia mendiamkanku. Ketika itu, tepat ketika aku berjuang melawan rasa sakit karena melahirkan , aku sempat berpikir, barangkali sebaiknya aku mati saja. Dengan begitu, selesailah semua penderitaanku. Aku menangis sembari menahan rasa sakit yang amat sangat. Aku begitu putus asa. Sungguh aku tak tahu lagi cara mengambil hati suamiku.
Tapi tangis bayi membuatku menarik keinginan itu. Bayi bermata indah itu membutuhkanku. Juga ketiga anakku yang lain. Aku harus hidup. Apapun yang terjadi.
Maka kupilih untuk bersabar. Kupikir lagi, barangkali kalau ada rizki dan aku bisa membawa suamiku berhaji, itu akan menjadi obat baginya, bagi kami. Maka itulah niatku.
Aku mulai mengumpulkan uang untuk bisa pergi haji.Aku ingin bermunajat pada Allah di tanah suci, agar aku bisa mendapatkan cinta suamiku. Aku juga ingin mendapat jawaban, mengapa aku tak lagi dicintai. Aku banyak berdoa, dan salah satu doa yang paling sering kuucapkan adalah: Allah humma arinal haqqa haqqan, warzuknatti ba’ah, wa arinal batiia batilan warzuknajtinabah (Ya Allah, tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berilah hamba kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan berilah hamba kekuatan untuk menjauhinya).